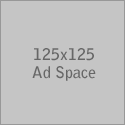Dirimu Apa Adanya
Gadis berjilbab ungu itu begitu manis, senyumnya begitu menawan, dan lesung pipinya sangat menarik hati. Gadis itu tengah bersandar pada pohon kelapa di kebun milik Pak Totok sembari membaca sebuah buku yang cukup tebal. Matanya yang dibingkai kacamata, menatap serius tiap halaman yang ia baca, sangat menawan. Seperti ada sebuah magnet yang membuat para lelaki seperti Arif tak bosan melihatnya berlama-lama. Arif sendiri hanya mampu memandanginya dari sudut terjauh yang mungkin tak dapat gadis itu lihat. Sebagai lelaki, tentu ia merasa seperti pecundang. Ia tak mampu menyampaikan perasaannya dengan gamblang. Jangankan menyampaikan perasaan, untuk mendekati dia saja tak bisa.
“Jangan seperti maling, Le. Kalau kamu suka, bilang saja suka,” ucap ibu sambil mengumpulkan buah kelapa yang sudah Arif petik. Lelaki itu terperanjat mendengar seruan ibu. Ia elus dadanya menenangkan jantung yang tiba-tiba saja berdetak begitu kencang.
“Arif bukan maling, Bu. Lagian mana berani Arif mencuri gadis semanis dan sesantun Shafa,”
“Loh, Shafa itu siapa? Ibu sepertinya kita tidak membicarakan nama itu sebelumnya,” Ucap ibu dengan nada jahil.
Arif masuk ke perangkap ibu. Ibunya itu memang gambaran wanita cerdas, mampu membaca anaknya dengan begitu baik. Semua yang dirasakan anak-anaknya, ibu pasti mengetahui sekecil apa pun itu.
“Arif bukan maling, Bu. Lagian mana berani Arif mencuri gadis semanis dan sesantun Shafa,”
“Loh, Shafa itu siapa? Ibu sepertinya kita tidak membicarakan nama itu sebelumnya,” Ucap ibu dengan nada jahil.
Arif masuk ke perangkap ibu. Ibunya itu memang gambaran wanita cerdas, mampu membaca anaknya dengan begitu baik. Semua yang dirasakan anak-anaknya, ibu pasti mengetahui sekecil apa pun itu.
“Bu, kelak ketika dewasa dan matang, Arif ingin meminang Shafa,” Ujarnya taktis. Ibu tiba-tiba saja berhenti menata buah kelapa. Beliau memandang lelaki itu lembut kemudian duduk di sampingnya. Tangan tuanya mengelus punggung Arif penuh sayang, seolah memberikan pengertian padanya. “Shafa memang gadis yang manis, cerdas, dan juga berperangai baik. Dia gadis yang rajin beribadah dan juga sopan terhadap orang yang lebih tua. Dia begitu paham terhadap hak dan kewajibannya dan dapat melaksanakannya dengan baik.”
“Dan kamu Le, anak Ibu tercinta. Dengan apa yang telah kau raih sekarang ini, apakah kau sudah merasa pantas bersanding dengan Shafa? Ibu ingin kamu introspeksi terlebih dahulu,” lanjut ibu.
“Dan kamu Le, anak Ibu tercinta. Dengan apa yang telah kau raih sekarang ini, apakah kau sudah merasa pantas bersanding dengan Shafa? Ibu ingin kamu introspeksi terlebih dahulu,” lanjut ibu.
Pikiran Arif mulai berputar. Ia membandingkan dirinya dengan Shafa. Berbeda. Mereka jauh berbeda. Ia merasa sangat timpang jika dibandingkan dengan Shafa. Mungkinkah ini pertanda kalau Shafa memang bukan jodohnya? “Nak, Ibu bicara demikian bukan untuk melunturkan semangatmu, tapi untuk membakar semangatmu. Pantaskanlah dirimu untuk Shafa, jadilah lelaki yang lebih baik dari ini sehingga mampu memimpin keluarga kalian nanti,” ibu tersenyum lembut. Arif ikut tersenyum melihatnya. Ibunya memang benar. Ia sama sekali belum pantas untuk bersanding dengan gadis itu. Ia peluk ibunya dengan penuh sayang sambil menatap Shafa dari kejauhan. Dan detik itu lelaki itu putuskan bahwa ia akan memantaskan diri. Merubah dirinya dan keadaan keluarganya menjadi lebih baik lagi.
Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kini Arif telah menjadi seorang arsitek yang sukses. Banyak bangunan bertingkat yang merupakan hasil desainnya. Perekonomiannya pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang ia mampu memperbaiki gubuk reotnya menjadi sebuah rumah yang layak tinggal. Selain itu, berjejer sepeda motor, sepeda, dan juga mobil di sana. Kehidupannya berubah cukup signifikan setelah empat tahun ia merantau. Lelaki itu kini tengah termenung di teras rumahnya. Ia tengah memikirkan keinginanya dahulu untuk menyunting Shafa. Ia bimbang dan terlalu takut untuk melakukan itu, karena ia merasa masih kurang pantas untuk mendampingi gadis yang sempurna di matanya itu.
“Kamu ini sedang memikirkan apa, Le?”
“Menurut Ibu, apakah sekarang ini Arif sudah pantas untuk Shafa?” ibu diam sejenak.
“Cobalah, Nak. Lamarlah Shafa terlebih dahulu. Dan kita bisa melihat apakah menurut Shafa kamu ini pantas untuknya atau tidak.” jelas sang ibu bijak.
Arif memikirkan pendapat ibunya dengan saksama. Ia merasa memang inilah saatnya ia mencoba melamar Shafa. Perjuangannya selama empat tahun memantaskan diri akan ditentukan sebentar lagi.
“Menurut Ibu, apakah sekarang ini Arif sudah pantas untuk Shafa?” ibu diam sejenak.
“Cobalah, Nak. Lamarlah Shafa terlebih dahulu. Dan kita bisa melihat apakah menurut Shafa kamu ini pantas untuknya atau tidak.” jelas sang ibu bijak.
Arif memikirkan pendapat ibunya dengan saksama. Ia merasa memang inilah saatnya ia mencoba melamar Shafa. Perjuangannya selama empat tahun memantaskan diri akan ditentukan sebentar lagi.
—
Arif melangkahkan kaki menuju rumahnya dengan rasa yang bercampur aduk. Napasnya ia hembuskan berat. Raut wajahnya muram dan tampak tak bersemangat. Sang ibu yang berjalan di belakangnya hanya menatap punggung anaknya itu dengan pasrah. Takdir memang tidak ada yang bisa menebak. Sekeras apa pun manusia berencana, segala kejadian hanya dapat diserahkan pada Tuhan.
“Duduklah dulu, Nak,” Tanpa membantah, Arif duduk di salah satu kursi kemudian mengusap wajahnya kasar.
“Ibu pernah berkata padamu bukan? Kalau Shafa memang jodohmu, dia pasti akan bersabar menunggumu. Tapi ternyata Shafa tidak menunggumu, jadi kamu harus menerima hal itu dengan hati yang lapang, Le,”
“Ibu pernah berkata padamu bukan? Kalau Shafa memang jodohmu, dia pasti akan bersabar menunggumu. Tapi ternyata Shafa tidak menunggumu, jadi kamu harus menerima hal itu dengan hati yang lapang, Le,”
“Arif ingin seperti itu, Bu. Namun rasanya sangat sulit. Semua yang Arif lakukan selama ini berawal untuk memantaskan diri sebagai pendamping Shafa… tapi…”
“Itu berarti Shafa memang bukan jodohmu, Le. Allah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu hanya harus lebih bersabar dan berusaha lebih keras. Ingat, gadis baik hanya untuk pria yang baik. Jadilah kamu lelaki baik, agar mendapatkan gadis baik yang melebihi Shafa.”
“Itu berarti Shafa memang bukan jodohmu, Le. Allah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu hanya harus lebih bersabar dan berusaha lebih keras. Ingat, gadis baik hanya untuk pria yang baik. Jadilah kamu lelaki baik, agar mendapatkan gadis baik yang melebihi Shafa.”
Kata-kata ibunya itu tidak berhasil menghibur Arif yang masih bersedih. Ingin sekali pria itu melupakan Shafa dan beralih mencari gadis yang ditakdirkan untuknya, namun sulit. Melupakan seorang gadis yang membuatnya berubah menjadi lebih baik sangat sulit dilakukannya. Ia hanya dapat merenung dan berdoa agar nasibnya menjadi lebih baik dari sekarang. Suara bel rumah membangunkan Arif dari lamunannya. Ia berdiri degan malas kemudian membuka pintu. Matanya membelalak ketika didapatinya Shafa di hadapannya berurai air mata dan sedikit terisak. Wajahnya sangat merah membuat Arif heran. Siapa yang sudah membuat gadis yang disukainya bersedih seperti ini?
“Mas Arif, maafkan Shafa. Maafkan Shafa yang tidak bisa menerima lamaran Mas Arif,” ucap gadis itu penuh dengan isakan. Arif mengernyitkan dahi melihat Shafa yang tampak begitu bersalah menolak lamarannya. Tadi memang ia tidak menolak secara langsung lamaran itu, hanya lewat ayahnya. Ia tak menyangka bahwa Shafa sangat begitu merasa bersalah. “Sudahlah, Shafa. Saya ikhlas lahir batin jika kamu menolak lamaran saya tadi. Saya tidak menyalahkanmu, karena sudah memang hakmu untuk memilih untuk menerima atau menolak saya.”
“Bu… bukan itu masalahnya, Mas. Ada satu dan lain hal yang membuat Shafa menolak Mas Arif.” Shafa menangis semakin terisak. “Shafa sudah tidak suci lagi, Mas!” pekik Shafa yang membuat Arif terkejut. Tangisan Shafa semakin keras memancing tetangga menonton kejadian di rumah Arif itu. Ibu Arif pun berdiri menyaksikan keduanya. Arif dan semua orang begitu terkejut mendengarnya. Mereka mengenal Shafa sebagai gadis baik-baik dan juga berakhlaq mulia. Rasa tidak percaya menyisip begitu saja ketika Shafa beicara demikian.
“Bagaimana bisa?” Arif menatap Shafa penuh tuntutan.
“Mas Adam yang melakukannya. Tidak lama setelah Mas Arif pergi dari desa ini, Mas Adam melakukan itu. Dan… dan…”
“Dan kau menerimanya begitu saja?” tanya Arif tak percaya.
“Mas, dengarkan Shafa dulu,”
“Mas Adam yang melakukannya. Tidak lama setelah Mas Arif pergi dari desa ini, Mas Adam melakukan itu. Dan… dan…”
“Dan kau menerimanya begitu saja?” tanya Arif tak percaya.
“Mas, dengarkan Shafa dulu,”
Arif melirik banyak tetangga yang menontoninya dan juga Shafa. Pandangan sinis terlihat jelas mereka tujukan pada Shafa setelah mendengar ceritanya. Bisik-bisik negatif pun ke luar dari mulut mereka, bahkan terdengar hingga telinganya. Tak tahan melihat Shafa dipandangi seperti itu, Arif meminta Shafa masuk ke rumahnya yang kemudian disusul oleh ibunya. Arif mempersilahkan Shafa duduk, sementara ibunya membuatkan teh hangat di dapur untuk gadis itu. Kedua tangan Shafa bergetar saat dilihatnya Arif menatapnya marah. Ia salah. Ia memang salah. Ia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ia memang tidak pantas untuk Arif. Ia yakin, pria itu sekarang jijik melihatnya yang sudah kotor.
“Tenanglah, jangan takut,” ujar Arif mencoba meredakan emosinya. Ia marah. Ia sangat marah pada Adam, kakak kandung Shafa sendiri. Kakak Shafa itu sama sekali tidak bermoral hingga melakukan hal keji itu pada adiknya sendiri. Arif sampai tak habis pikir apa yang ada dalam pikiran Adam hingga melakukan hal hina seperti itu.
“Aku merasa tidak pantas untukmu, Mas. Maafkan aku karena menolak lamaranmu. Tapi sungguh, setelah menolakmu hatiku terasa sangat sakit.” Jelasnya.
“Minumlah dahulu, Nak. Tenangkan dulu pikiranmu,” ibu Arif mengulurkan secangkir teh pada Shafa. Shafa menerimanya kemudian menyesap teh itu. Rasa hangat teh itu mengalir ke dalam tenggorokan, membuatnya sedikit tenang. Ia letakkan cangkir itu ke atas meja, dan menatap Arif lagi.
“Aku merasa tidak pantas untukmu, Mas. Maafkan aku karena menolak lamaranmu. Tapi sungguh, setelah menolakmu hatiku terasa sangat sakit.” Jelasnya.
“Minumlah dahulu, Nak. Tenangkan dulu pikiranmu,” ibu Arif mengulurkan secangkir teh pada Shafa. Shafa menerimanya kemudian menyesap teh itu. Rasa hangat teh itu mengalir ke dalam tenggorokan, membuatnya sedikit tenang. Ia letakkan cangkir itu ke atas meja, dan menatap Arif lagi.
“Kau tahu, Mas? Sekarang ini aku merasa seperti wanita murahan. Aku mengemis cintamu yang bahkan belum satu jam yang lalu aku tolak. Aku malu, Mas. Aku malu mengakui semuanya,” jelas Shafa dengan matanya yang kembali memerah.
“Terima kasih kamu sudah mau jujur pada saya. Saya tidak tahu jika masalahmu sebesar ini,”
“Jujur saja, saya sangat kaget ketika kau datang dengan kabar yang begitu mengejutkan. Di satu sisi saya sangat senang karena perasaan saya bukan cinta sepihak. Tapi di sisi lain, saya cukup kecewa, kenapa kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri.”
“Terima kasih kamu sudah mau jujur pada saya. Saya tidak tahu jika masalahmu sebesar ini,”
“Jujur saja, saya sangat kaget ketika kau datang dengan kabar yang begitu mengejutkan. Di satu sisi saya sangat senang karena perasaan saya bukan cinta sepihak. Tapi di sisi lain, saya cukup kecewa, kenapa kau tidak bisa menjaga dirimu sendiri.”
“Itu karena Mas Adam memaksaku, Mas. Dia merenggutku sesaat setelah aku… setelah aku melihatmu pergi di stasiun. Saat itu ia tengah mabuk karena kalah berj*di. Aku… aku…” Shafa menunduk malu sekaligus sedih. Ia menceritakan hal yang paling memalukan pada seorang yang dicintainya. Ia yakin, setelah ini Arif tidak akan mau melihatnya yang sudah kotor ini lagi. “Aku juga… aku sudah punya anak, Mas.” tambah Shafa yang begitu mengejutkan Arif.
Lelaki itu terperanjat mendengar penuturan Shafa. Hari ini gadis itu senang sekali memberinya kejutan. Setelah menolaknya, kemudian berkata bahwa menyukainya, lalu menyatakan jika dia sudah tidak suci, dan sekarang berkata sudah punya anak? Kejutan bertubi-tubi ini sulit dicernanya. Rasa cintanya seperti diuji sekarang. Dulu ia begitu mencintai Shafa dengan segala kesempurnaannya, namun kini ia dihadapkan pada kenyataan yang menohok hatinya. Bisakah ia mencintai Shafa sama seperti saat ia belum mengetahui semua fakta ini? Arif terdiam mendengarkan penjelasan Shafa selanjutnya. Rasanya menghakimi Shafa saat ini bukanlah hal yang pantas. Ia juga ikut andil dalam hal ini. Seandainya ia tidak pergi, ia yakin dapat menjaganya meskipun dalam kejauhan sekali pun.
“Namanya Wahyu. Saat ini dia berumur 3 tahun.”
“Kenapa Ibu tidak pernah tahu kau mengandung dan melahirkan? Dan… putramu itu, Ibu tidak pernah melihatnya.”
“Wahyu tinggal bersama Ibu saya di sebuah desa yang cukup jauh dari sini. Saya menyembunyikannya, menyembunyikan kelahirannya, dan menyembunyikan saat saya hamil karena saya takut Mas Arif… saya takut kelak ketika Mas Arif datang, dia membenci saya. Walaupun saya tahu sekarang ini dia sudah membenci saya setelah saya menceritakan semua ini,”
“Kenapa Ibu tidak pernah tahu kau mengandung dan melahirkan? Dan… putramu itu, Ibu tidak pernah melihatnya.”
“Wahyu tinggal bersama Ibu saya di sebuah desa yang cukup jauh dari sini. Saya menyembunyikannya, menyembunyikan kelahirannya, dan menyembunyikan saat saya hamil karena saya takut Mas Arif… saya takut kelak ketika Mas Arif datang, dia membenci saya. Walaupun saya tahu sekarang ini dia sudah membenci saya setelah saya menceritakan semua ini,”
Arif terhenyak. Anak? Tak pernah terpikir olehnya Shafa sudah memiliki anak. Ia marah. Rasa marahnya bukan karena Shafa telah memiliki anak, namun karena wanita itu menyembunyikan semua fakta yang ada. Ia sudah membohongi semua tetangga bahkan dirinya sendiri hanya untuk Arif. Pria itu sangat tidak menyukai kepura-puraan untuk suatu hal yang semu. “Apa alasanmu menceritakan semua ini? Kamu berkata mencintaiku, kemudian membeberkan semua fakta yang sangat… sangat mengagetkanku. Saya bingung. Saya marah, Shafa. Di mata saya kamu adalah seorang wanita yang baik dan berakhlaq mulia. Tapi…”
“Untuk itulah saya tadi menolak lamaran Mas Arif. Jikalau saya menerimanya, sama saja saya membohongi Mas Arif. Mas hanya tahu saya yang empat tahun yang lalu. Empat tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk terjadi berbagai hal yang mustahil terjadi. Dan dalam empat tahun itu memang terjadi hal yang sangat tidak terduga,” potong Shafa. “Maaf saya mengganggu Mas dengan segala fakta ini. Saya hanya ingin Mas Arif menerima Shafa yang sekarang dengan apa adanya saya, bukan Shafa yang empat tahun lalu. Semua keputusan ada pada Mas Arif. Shafa tidak akan memaksa.” pungkas Shafa.
Shafa sudah siap dengan semua keputusan Arif. Kalau beruntung, Arif masih mau menerimanya apa adanya. Namun, harapan itu tinggal harapan agaknya ketika melihat raut wajah Arif saat ini. Wajahnya merah seperti manahan amarah. Pun, ibu Arif. Beliau tampak sangat terkejut namun masih mampu mengontrol emosinya sendiri. “Lalu apa maumu sekarang?” Arif bertanya sinis.
Wanita itu kaget mendengarnya. Belum pernah ia mendengar Arif berucap sinis seperti itu. Ia menunduk takut. Ia sendiri bingung apa maunya. Di satu sisi ia ingin bersama Arif namun di sisi lain ia tak ingin Arif mendapat wanita semacam dirinya. “Shafa hanya ingin Mas Arif merasa adil. Shafa tidak ingin Mas Arif, Shafa tolak tanpa alasan yang jelas seperti tadi. Dan… Shafa rasa semua sudah dijelaskan. Maaf telah mengganggu Mas Arif.” Shafa berdiri kemudian menyalami ibu Arif dan beranjak dari kediaman Arif. Ia malu. Ia terlalu percaya diri jika Arif akan menerimanya apa adanya.
Seminggu sejak pengakuannya yang begitu mengejutkan, Shafa hidup layaknya seorang yang tak memiliki arah. Ia begitu lelah melakukan segala kewajibannya. Namun keberadaan anaknya mengahapus semua rasa lelah tersebut. Sekarang ini ia telah tinggal besama anaknya. Anaknya membutuhkannya. Ia tidak mau bersikap egois dengan menyingkirkan anaknya dari kehidupannya hanya untuk seorang lelaki yang kini membencinya.
Shafa menggandeng Wahyu mengelilingi halaman rumahnya. Balita kecil itu tampan, namun fisiknya kurang sempurna. Ia hanya mempunyai satu tangan utuh, yang membuatnya kesulitan melakukan berbagai hal. Namun Wahyu begitu aktif dan selalu membuat semangat Shafa kembali pada titik tertinggi dalam menjalani hidupnya. Saat tengah bercanda dengan Wahyu di halaman rumah, tiba-tiba saja muncul lelaki yang beberapa hari ini membuatnya bermuram durja. Lelaki itu datang bersama ibunya yang berpakaian sangat rapi. Shafa kemudian membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan tamunya itu masuk dan duduk.
“Maaf sebelumnya. Ada apa ya, Ibu dan Mas Arif datang ke mari?” Shafa bertanya penuh keraguan.
“Ayahmu ada? Saya ke mari untuk meminangmu, Shafa,”
Setelah mendengar itu, Shafa sadar dan percaya bahwa cinta yang tulus itu memang benar adanya.
“Ayahmu ada? Saya ke mari untuk meminangmu, Shafa,”
Setelah mendengar itu, Shafa sadar dan percaya bahwa cinta yang tulus itu memang benar adanya.
SELESAI